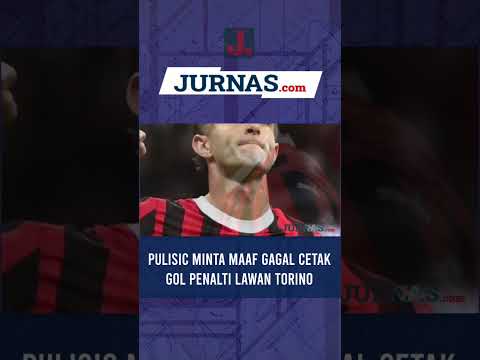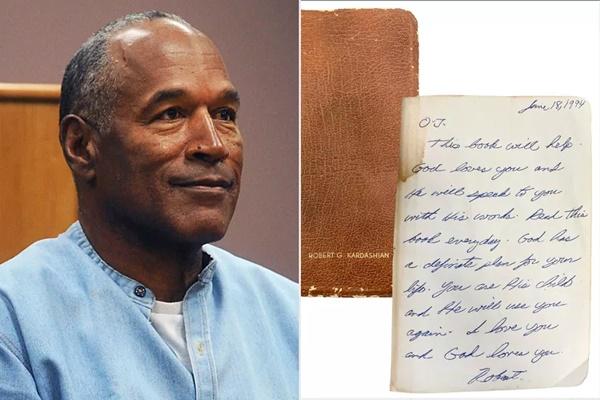Seorang wanita Palestina menggendong putrinya saat berjalan melewati reruntuhan rumah yang hancur akibat serangan militer Israel di Khan Younis pada 10 Juli 2024. (FOTO: REUTERS)
JAKARTA - Ketika perang Israel dimulai, keluarga-keluarga di Gaza menghadapi keputusan yang sulit untuk tetap tinggal di utara atau pergi ke selatan menuju "zona aman" yang diiklankan.
Banyak wanita yang pergi ke selatan, terkadang sendirian dengan anak-anak kecil, terpaksa meninggalkan suami mereka, tanpa mengetahui kapan keluarga mereka akan bersatu kembali.
Sejak Oktober, tentara Israel telah mendirikan pos pemeriksaan di Jalan Salah al-Din dan Jalan al-Rasheed – satu-satunya rute utama yang menghubungkan Gaza utara dan selatan – untuk mencegah pergerakan antar wilayah tersebut.
Nasib puluhan ribu orang yang mengungsi dari utara ke selatan masih diselimuti ketidakpastian.
Banyak yang mendambakan kepulangan cepat ke rumah dan orang-orang terkasih yang terpaksa mereka tinggalkan.
Berikut ini adalah kisah tiga perempuan yang mengalami pemisahan paksa:
"Apakah saya akan bertemu Abed lagi? Saya ragu": Raheel
Ketika konflik pertama kali dimulai, Raheel (27) yang baru menikah, patah hati karena harus meninggalkan suaminya, Abdel Kareem, yang juga dikenal sebagai "Abed", di Kota Gaza.
Namun, pasukan Israel menjanjikan pergerakan yang aman ke selatan, dan ayahnya bersikeras agar dia pergi.
“Saya takut perang. Tubuh saya gemetar setiap kali terjadi ledakan,” aku Raheel.
Dia mencari perlindungan di rumah bibinya di Nasser, sebuah lingkungan di bagian barat Kota Gaza.
Namun, pada tanggal 13 Oktober, selebaran tentara Israel mendesak warga sipil untuk mengungsi dari kota tersebut karena mereka berencana untuk "beroperasi secara signifikan" di sana dalam beberapa hari mendatang.
Mempercayai perintah tersebut, ayah Raheel bersikeras agar dia, lima saudara perempuannya, dua saudara laki-lakinya, dan ibu mereka pindah ke selatan, meskipun ia bermaksud untuk tetap tinggal di rumah di lingkungan Tuffah.
“Kamu harus berada di mana pun saudara perempuanmu berada,” katanya.
Meskipun wilayah selatan dianggap aman, Raheel bimbang untuk meninggalkan kota itu. Gangguan komunikasi menyebabkan dia tidak dapat memberitahu suaminya yang tinggal bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia – mereka tidak dapat melakukan perjalanan ke selatan.
Raheel akhirnya pergi tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Abdel Kareem.
“Saya pikir ini hanya masalah waktu, dan saya akan segera kembali ke rumah,” jelasnya.
“Saya tidak tahu perang akan berlangsung selama ini, tanpa ada tanda-tanda akan berakhir,” seraya menambahkan bahwa, “Saya pikir pergi ke selatan akan melindungi saya.”
Perjalanan Raheel ke selatan dipenuhi rasa takut dan ketidakpastian. Berpindah dari Kota Gaza ke Khan Younis, Rafah ke al-Mawasi, lalu kembali lagi ke Khan Younis, ia menghadapi kesulitan akibat pengungsian paksa dan hidup di tempat penampungan yang penuh sesak dengan sumber daya yang terbatas.
Setiap kali ia melangkah menjauh dari rumah, Raheel merasakan beban berat perpisahannya dengan suami dan ayahnya.
Kekhawatiran tentang orang-orang yang dicintainya yang menderita kekurangan pangan yang parah serta serangan dan pemboman sewenang-wenang Israel semakin memperkuat keputusasaannya.
Menikah setahun sebelum perang, Raheel pernah bermimpi untuk memulai sebuah keluarga. Namun, ia menemukan pelipur lara dalam ketidakberdayaannya di tengah kekacauan tersebut.
“Setiap hari saya bersyukur kepada Tuhan karena saya tidak perlu khawatir tentang bayi dalam kondisi seperti ini. Ketakutan itu tidak akan tertahankan,” ungkapnya.
Pada bulan Juni, dia mengetahui bahwa saudara iparnya terbunuh dalam operasi militer di Shujayea di Kota Gaza.
"Untuk pertama kalinya, saya berharap tetap tinggal di Kota Gaza untuk mendukung suami saya," kata Raheel.
"Saya merasa tidak berdaya karena berada jauh darinya. Apakah saya akan pernah bertemu Abed? Saya ragu."
Banyak malam, ketika komunikasi terputus, Raheel terjaga, air mata mengalir di wajahnya saat ia menggenggam telepon genggamnya dan berdoa agar mendapat pesan dari suami atau ayahnya.
Suara bom di kejauhan menjadi pengingat akan bahaya yang mereka hadapi.
"Saya tidak dapat menggambarkan rasa sakit karena tidak tahu apakah mereka aman atau apakah saya akan pernah melihat mereka lagi," katanya.
Meskipun dalam keadaan yang buruk, Raheel tetap tangguh, mengambil peran sebagai pengasuh dan pelindung bagi ibu dan saudara perempuannya — meskipun hatinya sendiri hancur.
“Saya harus tetap kuat untuk mereka,” katanya. “Kita harus percaya bahwa suatu hari nanti, kita akan dipersatukan kembali dengan orang-orang yang kita cintai dan membangun kembali kehidupan kita.”
`Tidak mengetahui nasibnya adalah bagian tersulit`: Walaa
Walaa, seorang ibu tiga anak, menghadapi dilema yang sama. Didesak oleh suaminya untuk mencari tempat yang aman bagi anak-anak mereka yang masih kecil, mereka semua meninggalkan rumah mereka di kamp pengungsi Shati, yang juga dikenal sebagai Kamp Pantai, di bagian barat Kota Gaza menuju rumah seorang kerabat di bagian tengah Gaza.
Setelah mengalami pengeboman yang tiada henti, pasangan itu merasa gelisah apakah akan tetap bersama atau berpisah demi keselamatan.
Pada tanggal 14 November, Walaa membawa anak-anak mereka ke selatan sementara suaminya, Ahmed, tinggal untuk merawat ayahnya yang terluka.
Di Gaza selatan, Walaa yang berusia 31 tahun berjuang. Ia harus menjadi ibu sekaligus ayah sambil menghadapi kesulitan hidup dan keterbatasan sumber daya di Gaza selatan.
“Tidak ada yang bisa merawat anak-anak saya seperti orang tua mereka,” katanya.
“Setiap malam, mereka menangis, ingin melihat ayah mereka dan memastikan keselamatannya. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba menenangkan mereka.”
Pemutusan komunikasi membuat komunikasi menjadi hampir mustahil.
Anak-anak sering bertanya tentang ayah mereka, kepolosan mereka menusuk hati Walaa.
Dia mencoba menghibur mereka, meyakinkan mereka bahwa mereka akan segera bersatu kembali, tetapi dia sendiri menyimpan keraguan.
“Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka merindukan ayah mereka, dan saya mengatakan kepada mereka bahwa saya juga merindukannya. Tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan,” katanya dengan nada putus asa.
Sering kali, Walaa tidak bisa tidur karena dihantui kekhawatiran akan suaminya.
"Saya merasa ada bagian dari diri saya yang hilang," akunya. "Tidak mengetahui nasibnya adalah bagian tersulit."
Setelah delapan bulan berpisah, gagasan untuk bersatu kembali dengan suaminya telah menjadi mimpi yang jauh.
“Saya merasa menyesal. Saya menyesali hari ketika kami memutuskan untuk meninggalkan wilayah utara,” keluh Walaa.
Doaa: `Saya melihat mereka memukuli suami saya dan menyeretnya pergi`
Tidak seperti Walaa dan Raheel, Doaa dan suaminya Abdullah memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza utara, karena yakin tidak ada tempat yang benar-benar aman. Mereka pindah dari rumah mereka di dekat Pelabuhan Gaza ke daerah dekat Lapangan Yarmouk di lingkungan Jalaa.
Meskipun tank-tank Israel terus maju, pasangan itu yakin status sipil mereka akan melindungi mereka, jadi mereka tetap tinggal di tempat itu.
"Kami tidak punya hubungan apa pun dengan Hamas atau pihak mana pun," Doaa menegaskan.
Harapan mereka hancur ketika tentara Israel menyerbu daerah itu, meneror wanita dan anak-anak, menyiksa orang tua, dan menculik para pria.
Di tempat mereka menginap, Doaa menyaksikan Abdullah, ayah mertuanya, dan saudara iparnya disiksa dan dibawa pergi.
Kenangan hari itu menghantuinya. "Mereka menyerbu masuk tanpa peringatan," kenangnya, suaranya bergetar.
"Saya melihat mereka memukuli suami saya dan menyeretnya pergi. Ayah mertua saya juga diculik. Kami tidak berdaya."
Selama hampir 60 hari, Doaa tidak berhubungan dengan Abdullah, yang dipindahkan ke penjara Israel. Ketidakpastian dan ketakutan menggerogoti dirinya setiap hari.
“Malam-malam adalah saat yang paling sulit,” katanya. “Saya tidak bisa tidur, membayangkan semua kengerian yang mungkin akan dihadapinya.”
Ketika akhirnya dibebaskan di selatan, Doaa dan putrinya yang berusia hampir 21 bulan masih berada di utara. Namun, tentara Israel tidak mengizinkan siapa pun bepergian ke Gaza utara.
"Lolo hampir berusia satu tahun ketika ditangkap. Saya ragu dia akan mengenalinya jika dia melihatnya," kata Doaa, air mata mengalir di matanya.
Beradaptasi dengan kenyataan hidup yang keras tanpanya, Doaa menjadi satu-satunya pengasuh dan penyedia nafkah bagi putri mereka.
Tanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan Lolo sangat besar. “Saya harus kuat untuknya,” jelas Doaa. “Tidak ada pilihan lain.”
Ia bergantung pada keluarganya, yang terus menemaninya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menghindari kematian di wilayah utara Gaza.
Saat hati Doaa pedih ingin segera bertemu suaminya, ia juga berduka atas rumah indah mereka yang hancur akibat serangan Israel. Segalanya, katanya, mengingatkannya pada suaminya.
“Kami terus maju karena kami harus melakukannya,” kata Doaa. “Demi anak-anak dan keluarga kami, kami tidak punya pilihan lain.” (*)
KEYWORD :
Israel Teroris Israel Gaza wanita keluarga pengungsi Palestina